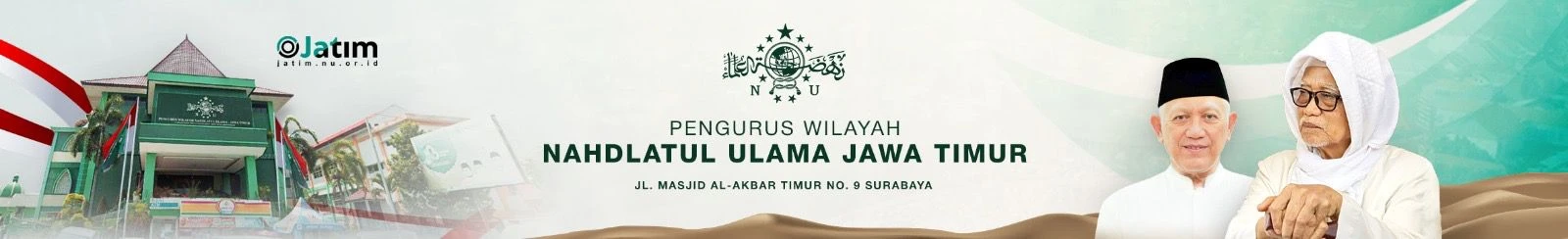Oleh: M. Syahri Romadhon*
Bahasa Arab dengan segala keunikannya memiliki berbagai kerumitan. Keunikannya di antaranya adalah memiliki sistem tanda diakritik (harakat) yang menjadi pembantu bagi pembacanya agar terhindar dari salah baca.
Mirip dengan Aksara Jawa dengan sandhangannya (wulu, suku, taling, taling tarung, pepet). Bedanya, pemberian sandhangan dalam Aksara Jawa merupakan suatu keharusan untuk mengubah huruf vokal. Sedangkan pemberian harakat dalam bahasa Arab bersifat opsional.
Adapun kerumitannya di antaranya adalah pembacanya dituntut untuk menguasai seperangkat kaidah yang melekat kepadanya, yaitu ilmu sharf (untuk menuntun bacaan yang benar dari segi kata) dan ilmu nahwu (untuk menuntun bacaan yang benar antar kalimat yang kebanyakan fokus pada bacaan akhir suatu kata).
Dengan kedua ilmu ini, pembaca sudah mempunyai ‘bekal’ untuk membaca dengan benar. Namun terkadang belum mampu untuk sampai ke gerbang ‘pemahaman yang komprehensif’ jika tidak mempelajari ilmu Balaghah (disiplin ilmu yang berfungsi untuk mengetahui hikmah yang tersembunyi dari suatu kalimat).
Tidak hanya itu, bahasa Arab juga sangat bergantung pada konteks, misalnya lafadz كتب yang memungkinkan dibaca “kataba” (menulis), “kutiba” (ditulis), atau “kutub” (kitab-kitab). Tergantung makna apa yang dikehendaki berdasarkan konteks (contextual purpose). Tentu ini berbeda dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang penulisannya menggunakan alfabet Latin, yang sudah bisa dibaca tanpa memerlukan konteks.
Dalam penentuan suatu hukum yurisprudensi Islam (fiqh), bahasa Arab memainkan peranan yang sangat penting. Bagaimana tidak, sumber yurisprudensi tersebut ditulis menggunakan bahasa Arab. Oleh karenanya, tak jarang kita jumpai perbedaan madzhab dalam suatu masalah. Misalnya adalah ayat tentang wudlu’:
یَـٰۤأَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُوۤا۟ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُوا۟ وُجُوهَكُمۡ وَأَیۡدِیَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَیۡنِۚ... الآية (المائدة: 6)
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki… dst (Q.S. Al-Ma’idah: 6)
Ayat ini menyebutkan tata cara wudlu’ yang meliputi 4 hal:
1. Membasuh wajah
2. Membasuh kedua tangan beserta siku
3. Mengusap kepala
4. Membasuh kedua kaki beserta mata kaki
Keempat fardlu yang disebutkan dalam ayat ini disepakati (muttafaq ‘alaih) oleh keempat madzhab. Namun mereka berbeda pendapat (mukhtalaf fiih) terkait kadar mengusap kepala ketika wudlu’.
Madzhab Maliki dan madzhab Hanbali berpendapat bahwa yang menjadi fardlu wudlu’ adalah mengusap seluruh kepala. Sedangkan madzhab Hanafi dan madzhab Syafi’i berpendapat cukup sebagian kepala, adapun mengusap seluruh kepala itu sunnah (Al-Juzairy, 2016).
Lebih lanjut, madzhab Hanafi dan madzhab Syafi’i pun beda pendapat terkait batas minimal mengusap sebagian kepala. Madzhab Hanafi berpendapat minimal seperempat kepala (rubu’ ar-ra’si), yakni kira-kira seukuran telapak tangan (miqdaaru kaffi al-yad).
Sedangkan madzhab Syafi’i berpendapat cukup sebagian saja, walaupun hanya sedikit. Bahkan jika hanya mengusap sebagian dari satu helai rambut kepala (ba’dh sya’rotin waahidah) itu sudah mencukupi. Asalkan rambut tersebut tidak keluar dari batas kepala (hadd ar-ra’si). Jika rambut seseorang panjang hingga sampai pundak, misalkan, lalu ia hanya mengusap ujung rambutnya, maka itu tidak sah, karena telah keluar dari batas kepala (Ad-Dimyathy, 1997; Al-Malibary, 2010).
Jika ditelisik lebih jauh, perbedaan keempat imam madzhab di atas adalah terkait interpretasi huruf ba’ dalam ayat (وَٱمۡسَحُوا۟ بِرُءُوسِكُمۡ). Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa ba’ tersebut adalah ba’ za’idah/tambahan yang tidak memberikan efek apapun dalam segi makna. Yakni, keberadaan ba’ di situ seakan-akan seperti ketiadaanya (wujuuduhu ka ‘adamihi). Sehingga tetap memberikan kesan makna “usaplah (seluruh) kepalamu”.
Kontras dengan hal itu, Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa ba’ tersebut mempunyai fungsi makna huruf jar “min” at-tab’idhiyyah (مِنْ التبعيضية). Sehingga memberikan kesan makna “sebagian”. Sebagaimana ayat "عَيناً يشربُ بها عبادُ اللهِ" yang mana ba’ di situ juga bermakna “min” at-tab’idhiyyah, yakni منها.
Tentu pendapat keempat imam madzhab tersebut tak lepas dari landasan kuat dari hadist-hadist Nabi. Sayyid Bakri bin Muhammad Syatho (pengarang kitab I’anah at-Thalibin) juga memberi penjelasan lebih lanjut mendukung pendapat ini:
*(فامسحوا برؤوسكم)* ووجه دلالتها على الاكتفاء بمسح البعض أن الباء إذا دخلت على متعدد - كما في الآية - تكون للتبعيض، أو على غير متعدد كما في قوله تعالى: * (وليطوفوا بالبيت العتيق) * تكون للإلصاق (إعانة الطالبين: ج 1، ص 52).
Ayat (فامسحوا برؤوسكم): Alasan indikasi cukup dengan mengusap sebagian adalah karena jika huruf ba’ masuk ke dalam bentuk jamak – seperti dalam ayat tersebut – maka itu berfungsi tab’idh (sebagian). Jika masuk ke dalam bentuk non-jamak, seperti dalam firman Allah: (وليطوفوا بالبيت العتيق) maka berfungsi ilshaq (bertaut/menempel) (Ad-Dimyathy, 1997).
Begitupun dengan tartib (urutan) wudlu’. Madzhab Hanafi dan madzhab Maliki sepakat bahwa tartib dalam wudhu’ itu bukan termasuk fardlu wudlu, melainkan sunnah. Sedangkan madzhab Syafi’i dan madzhab Hanbali berpendapat tartib itu termasuk fardlu. Yakni jika tidak tartib, maka wudlu’nya batal.
Jika ditinjau lebih dalam, perbedaan dua kubu madzhab ini terletak pada huruf wawu athaf dalam ayat wudlu di atas. Ditinjau dari segi nahwu, wawu athaf menurut madzhab Bashrah berfungsi untuk memutlakkan (li-muthlaq al-jam’i). Sehingga antara ma’thuf alaih (kalimat sebelum wawu athaf) dan ma’thuf (kalimat sesudah wawu athaf) itu mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada ketentuan khusus mana yang berhak didahulukan atau yang diakhirkan. Sehingga ini mendukung pendapat madzhab yang tidak memasukkan tartib dalam fardlu wudlu’.
Dalam arti, wudlu dengan mendahulukan tangan kemudian wajah, atau kaki kemudian tangan, itu tetap sah. Dikarenakan tartib itu bukan fardlu, melainkan sunnah. Sedangkan menurut madzhab Kufah, wawu athaf itu berfungsi untuk mengurutkan (lit-tartib). Sehingga memberikan kesan bahwa berwudlu’ itu harus urut sesuai tuntunan ayat wudlu’ di atas. Pendapat ini mendukung madzhab yang memasukkan tartib dalam fardlu wudlu’ (Ibnu Aqil, 2010; Ibnu Malik, 2010).
Oleh karena itu, tak mengherankan jika Imam Syafi’i hingga menekuni bahasa Arab selama 20 tahun hanya agar beliau terbantu untuk memahami Fiqih (hukum dalam Al-Qur`an Al-Karim dan As-Sunnah) (Al-Baghdady, 2010).
Referensi:
Ad-Dimyathy, A. B. bin M. S. (1997). I’anah At-Thalibin (1st ed.). Dar el Fikr.
Al-Baghdady, A.-K. (2010). Al-Faqih wa Al-Mutafaqqih. Dar Ibni Al-Jauzy.
Al-Juzairy, A. (2016). Al-Fiqh ’Ala Al-Madzahib Al-Arba’ah (2nd ed.). Dar Alamiyyah.
Al-Malibary, Z. A. (2010). Fathul Mu’in (1st ed.). Dar Ibni Hazm.
Ibnu Aqil, A. bin A. (2010). Syarh Ibni Aqil ala Alfiyah Ibni Malik. Dar Turats.
Ibnu Malik, M. bin A. (2010). Alfiyah Ibni Malik. Dar Ta’awun.
*Pengajar dan alumni PP. Miftahul Huda Gadingkasri Klojen Malang
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Merayakan Maulid Nabi, Meneladani 4 Sifat Rasulullah
2
Haul ke-44 Mbah Hamid Pasuruan, Berikut Rangkaian Acaranya
3
Solidaritas Ojol: Ribuan Pengemudi Iringi Pemakaman Affan yang Meninggal dalam Demo
4
PBNU Minta Maaf Telah Datangkan Peter Berkowitz: Khilaf dan Kurang Cermat
5
Yudisium Angkatan 2021, Fakultas Pertanian Unisda Bersama Mahasiswa RPL
6
Rais PCNU Sidoarjo Ajak Nahdliyin Lestarikan Tradisi Maulid Nabi
Terkini
Lihat Semua