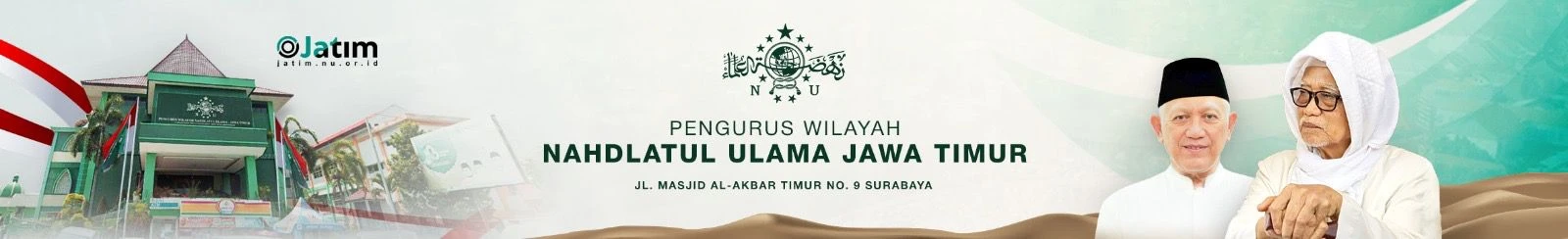Menimbang Ulang Tradisi Tunangan di Pedesaan Perspektif Agama dan Sosiologi
Rabu, 23 Juli 2025 | 19:00 WIB
Oleh: Dr. Abdul Wasik, M.HI *)
Prosesi tunangan di masyarakat pedesaan Indonesia sering kali menjadi momen penting yang tidak hanya menyatukan dua insan, tetapi juga menjadi ajang pertunjukan status sosial antar keluarga. Dalam kenyataan di lapangan, praktik lamaran ini kerap menampilkan seremonial besar, iring-iringan kue dan buah, bingkisan sandang, hingga sajian makan yang tampak mewah. Padahal, di balik kemeriahan itu, tersembunyi beban sosial dan ekonomi yang tidak sedikit.
Sebagian masyarakat menganggap banyaknya bawaan lamaran adalah bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan. Namun, yang sering terjadi justru adalah standardisasi adat yang membebani. Keluarga laki-laki dituntut membawa makanan dalam jumlah dan jenis tertentu, demi “layak secara sosial”, bukan karena kebutuhan substansial.
Dalam perspektif Pierre Bourdieu, praktik ini merupakan bentuk distingsi —yaitu cara keluarga menunjukkan kelas sosial dan mempertegas stratifikasi budaya. Makanan dan hadiah dalam lamaran menjadi modal simbolik untuk mendapatkan legitimasi sosial. Sayangnya, ini kerap mengarah pada penindasan budaya secara halus, terutama bagi keluarga dari kelas ekonomi bawah yang merasa “tidak pantas” hanya karena tidak mampu tampil mewah.
Senada dengan itu, Thorstein Veblen menyebut fenomena ini sebagai conspicuous consumption —yakni konsumsi yang dilakukan bukan untuk kebutuhan, melainkan untuk menunjukkan kekayaan dan kehormatan. Maka, dalam banyak kasus, tunangan menjadi ajang "pamer" ketimbang penyatuan nilai-nilai sakral.
Kesederhanaan dalam Perspektif Islam
Jika kembali kepada syariat Islam, lamaran atau khitbah hanyalah proses permintaan menikah dari laki-laki kepada wali perempuan. Ia tidak mengikat secara hukum syar’i seperti akad nikah, dan tidak pula disyaratkan dengan bentuk dan isi hantaran tertentu.
Rasulullah SAW pernah bersabda: "Nikah yang paling besar keberkahannya adalah yang paling ringan maharnya."(HR. Ahmad, Abu Dawud, Hakim)
Lebih dari itu, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Isra’: 26–27: "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan." Dan dalam QS. Al-Furqān: 67: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian." Prinsip wasatiyyah (moderat) menjadi kunci utama dalam pengeluaran, termasuk untuk urusan tunangan. Islam mengajarkan agar kehidupan, termasuk peristiwa sosial seperti khitbah, tidak menjadi ajang pemborosan dan tekanan sosial.
Kritik Struktural dan Peluang Perubahan
Melalui kacamata Anthony Giddens, tradisi seperti ini tidak harus diterima sebagai takdir sosial. Masyarakat sebenarnya memiliki agensi untuk mengubah struktur yang telah lama membentuknya. Mereka dapat melakukan negosiasi ulang terhadap nilai-nilai budaya agar tetap berjalan tanpa memberatkan.
Sementara itu, Emile Durkheim menjelaskan bahwa tradisi kolektif berfungsi memperkuat solidaritas masyarakat. Namun, jika bentuk ritual justru memicu ketimpangan dan beban sosial, maka ia telah kehilangan fungsinya sebagai pemersatu dan malah menjadi alat eksklusi.
Dalam konteks Indonesia, kita juga dapat merujuk pada pendekatan sosiologi Islam-nusantara yang menganjurkan transformasi budaya melalui pendekatan ta’dīb (edukatif), bukan pemutusan paksa. Maka, solusi tidak terletak pada penghapusan tradisi, tapi pada pengelolaan nilai agar lebih rasional dan maslahat.
KH Afifuddin Muhajir —ulama fikih dan ushul fikih NU— menegaskan bahwa: “Segala adat boleh dijalankan selama tidak bertentangan dengan maqaṣid syari'ah. Jika menimbulkan mudarat, maka harus dikaji ulang dan diperbaiki.”
Inilah ijtihad budaya, yakni kemampuan umat Islam untuk memfilter tradisi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Tradisi boleh dijalankan, tapi jangan sampai menimbulkan kesulitan (masyaqqah) atau ketimpangan sosial yang bertentangan dengan maqaṣid seperti ḥifẓ al-māl (menjaga harta) dan ḥifẓ al-‘ird (menjaga kehormatan keluarga).
Tunangan adalah bagian dari perjalanan sakral menuju pernikahan. Ia mestinya menjadi momen menguatkan niat dan restu, bukan arena gengsi yang membebani. Dengan membaca ulang tradisi ini melalui lensa agama dan sosiologi, kita diajak untuk menjaga yang baik dari adat, sekaligus mengkritisi yang memberatkan.
Mari kita ubah budaya tunangan dari sekadar ritual simbolik yang mahal, menjadi peristiwa spiritual dan sosial yang ringan namun bermakna. Karena sejatinya, keberkahan rumah tangga tidak ditentukan oleh banyaknya kue hantaran, tetapi oleh niat suci, doa orang tua, dan kesungguhan untuk membangun rumah tangga yang sakinah.
*) Dr. Abdul Wasik, M.HI, pengurus RMI PWNU Jawa Timur dan dosen Islam di Institut Agama Islam At-Taqwa Bondowoso.
Terpopuler
1
Ratusan Jamaah Ikuti Baiat Thariqah Syadziliyah di Pondok Jajar Trenggalek
2
Resmi Dikukuhkan, Digdaya Digital dan Ekonomi Jadi Tema Besar GP Ansor Sidoarjo
3
ISNU Pasuruan Resmi Luncurkan Buku Biografi KH Achmad Muzayyin Zain
4
Ketua PW GP Ansor Jatim: Jangan Lewatkan Amanah yang Diberikan Para Muassis NU
5
Mengenal Mobile Unusa Incinerator, Alat Mengolah Air Bersih Layak Konsumsi
6
Gus Rikza Sebutkan Dua Cobaan Bagi Pengamal Thariqah
Terkini
Lihat Semua